Wabah Black Death di Era Khilafah Utsmani, Tak Lagi Apokaliptik
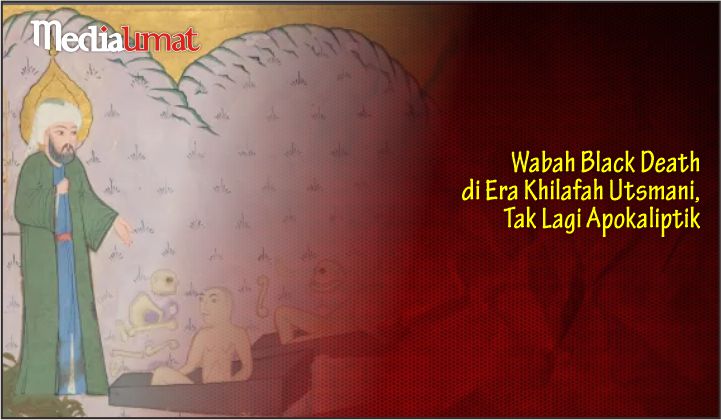
Mediaumat.id – Kendati penjangkitan wabah berulang sepanjang sejarah Ottoman (istilah Barat menyebut Kekhilafahan Utsmaniah), yang dimulai dengan pandemi Black Death pada tahun 1347 dan berlangsung hingga tahun 1947 M di Turki modern, faktanya pada akhir abad ke-16 wabah tak lagi dipandang sebagai fenomena apokaliptik yang tak terkendali oleh masyarakat setempat.
“Dimulai pada akhir abad ke-16, wabah tidak lagi dipandang sebagai fenomena apokaliptik yang tak terkendali,” ujar Nukhet Varlik, salah satu ahli terkemuka yang memahami bahwa Black Death yang juga berdampak pada Kekhalifahan Utsmaniah, seperti dikutip dari trtworld.com, (30/3/2020) silam.
Menurutnya, yang juga seorang penulis buku Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347–1600, seperti halnya Eropa, wilayah Kekhilafahan Utsmaniah juga tak luput dari Black Death. yang disebut juga sebagai Maut Hitam atau Wabah Hitam yang merupakan pandemi paling fatal yang pernah tercatat dalam sejarah manusia.
Kata Varlik, wabah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ini mengakibatkan kematian sekitar 75 juta hingga 200 juta orang-orang di Eurasia dan Afrika Utara. Pandemi ini memuncak di Eropa sejak tahun 1347 hingga 1351.
Kata dia lagi, meski banyak yang telah mempelajari wabah di Eropa dan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan politik, tetapi lebih sedikit yang mempelajari kejadian wabah di wilayah Kekhilafahan Utsmaniah.
Terlepas itu, adalah wabah maupun pandemi yang justru sudah dilihat oleh masyarakat Utsmani sebagai penyakit yang diakibatkan oleh sebab-sebab alami. Misalnya, kota yang tidak sehat dan dari sesuatu yang sebenarnya dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Padahal, terkait dengan faktor penyebab wabah karena bakteriologi modern, serta gagasan bahwa penyakit menular disebabkan oleh kuman yang tidak terlihat misalnya, baru berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu menjelang akhir sejarah kekhilafahan.
Sebutlah teori penyakit yang dominan mengaitkan penyebab penyakit epidemik dengan miasma, yaitu bau busuk yang diyakini mencemari udara dan membuat orang sakit.
Bahkan meski gagasan contagion (bahwa penyakit dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, secara langsung atau tidak langsung) diketahui dan dianut oleh sebagian orang, ujar Varlik, tidak memotivasi masyarakat Utsmani untuk melakukan pembatasan sosial (social distancing).
“Hal ini malah membuat mereka meninggalkan kota menuju tempat dengan udara bersih dan sehat. Namun, perpindahan ini sebagian besar terbatas pada kalangan elite,” bebernya.
Akrab
Untuk diketahui pula, cara berpikir masyarakat Utsmani sebelumnya tentang wabah, berubah seiring waktu. “Secara umum pada abad-abad pertama sejarah Ottoman, wabah dipahami sebagai keputusan ilahi, pertanda kiamat, dan akibat dari pelanggaran sosial dan moral,” tandasnya.
Artinya, sejak wabah berlanjut di Kekhilafahan Utsmaniah selama enam abad, penduduk menjadi lebih akrab dengan penyakit ini sebagai masalah yang berulang, hampir musiman, dan lantas mencari cara untuk melindungi diri dengan menggunakan obat-obatan dan doa misalnya.
Ia mengungkapkan, pada abad ke-19, Kekhilafahan Utsmani mendirikan stasiun karantina untuk tujuan mengendalikan dan mendesinfeksi individu dan barang yang memasuki perbatasannya.
Dengan kata lain, wabah dimaknai sebagai masalah yang berulang, berikut orang-orang akrab dengan tanda, gejala, dan perilakunya. “Masyarakat Ottoman jadi lebih bisa menebak kapan wabah akan dimulai, berapa lama akan berlangsung, berapa banyak yang akan mati, dan sebagainya,” paparnya.
Untuk itu, menjaga kebersihan jalan seperti menyingkirkan sampah dan mengaspal, serta memindahkan usaha-usaha seperti penyamakan kulit atau rumah jagal di luar tembok kota, karena dianggap mencemari udara, menjadi di antara bentuk-bentuk pembiasaan tersebut.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa Kekhilafahan Utsmaniah kala itu juga menawarkan keringanan pajak kepada individu dan komunitas yang terkena wabah dan mempromosikan pengembangan layanan kesehatan.
Institusi dan praktik yang berkembang pada abad ke-16 ini berlanjut dalam satu atau lain bentuk melalui periode modernisasi pada abad ke-19. “Oleh karena itu, rangkaian wabah ini jelas berdampak besar pada negara Ottoman, terutama di bidang kesehatan masyarakat,” bebernya.
Malah ia memandang, pada awal abad ke-16, pemerintahan pusat Utsmaniah mulai mengembangkan peraturan baru untuk penguburan korban wabah di Istanbul dan kota-kota lain, saat kematian akibat wabah melonjak.
Sebutlah layanan untuk industri pemakaman, berupa kuburan komunal baru di luar tembok kota dilengkapi dengan catatan jumlah korban tewas setiap hari.
Lantas menjawab seputar penutupan masjid atau kegiatan salat Jumat, ia pun menyampaikan bahwa ia tidak menemukan fenomena pembatasan sosial (social distancing).
“Saya tidak ingat menemukan referensi untuk fenomena ini di sumbernya. Sebaliknya, kita melihat contoh doa bersama yang diselenggarakan untuk mengangkat wabah,” jawab Varlik.
Salah satu contoh terkenal berasal dari masa pemerintahan Mehmed III (1595–1603). Kala itu, ungkapnya, para pejabat negara, tokoh agama, anggota kelompok sufi, dan orang-orang Istanbul berkumpul di Okmeydani untuk berdoa agar wabah dicabut.[] Zainul Krian


