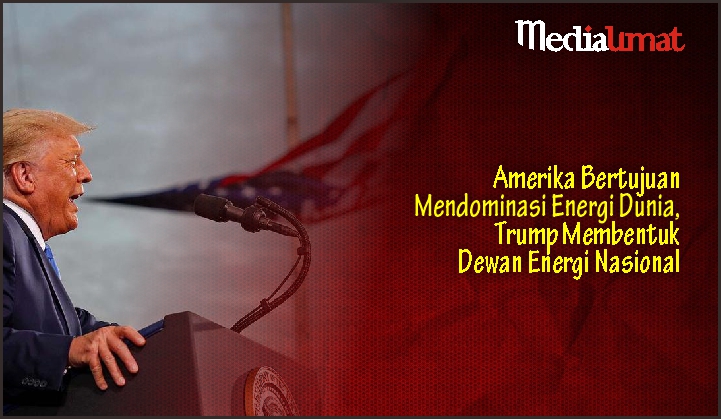Trump dan Masa Transisi AS

Masalah transisi terus berlanjut di Amerika, karena Presiden AS Donald Trump masih tetap menolak untuk mengakui bahwa dia kalah dalam pilpres dan bahwa lawannya Joe Biden sekarang adalah Presiden Terpilih. Hal ini bukanlah konsekuensi dari kerusakan sistem itu sendiri. Sistem pemilu AS selalu seperti ini, sengaja dirancang dengan ambiguitas yang tertanam, untuk memberikan ‘brankas’ bagi lembaga untuk melakukan intervensi jika perlu, seperti electoral college. Namun perbedaan nyata kali ini adalah polarisasi yang dalam di kalangan pemilih Amerika. Donald Trump telah mendapatkan jumlah suara tertinggi dalam sejarah Amerika untuk seorang kandidat presiden yang kalah.
Faktanya, dengan lebih dari 70 juta suara, dia telah menerima lebih suara dari setiap Presiden AS yang menang sebelum Biden, yang menerima 75 juta suara. Para pemimpin politik di Amerika ragu-ragu untuk mengkritik Trump karena takut menyinggung perasaan orang-orang yang telah memilihnya.
Meningkatnya polarisasi politik tidak hanya terjadi di Amerika tetapi pada umumnya terjadi di mana pun demokrasi liberal diterapkan. Ini karena para penguasa harus pergi ke tempat pemungutan suara berulang kali, untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan basis suara yang cukup besar. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membangun partisan inti di dalam pemilih. Trump telah mencontohkan pendekatan ini, dengan terus memelihara basisnya selama empat tahun, tetapi semua pemimpin demokrasi melakukan hal ini sampai taraf tertentu. Secara alami seiring waktu, hasil suara yang tak terhindarkan adalah adanya keberpihakan yang mendalam di dalam para pemilih. Islam menghindari keberpihakan dengan menjadikan Khalifah dipilih hanya sekali, dimana hal ini dilakukan hanya dalam jangka tiga hari yang tidak menyisakan waktu untuk membangun partisan yang kuat. Faktanya, peluang terkuat seorang kandidat untuk menang adalah dengan menarik semua orang untuk memilihnya.[]