Menyoal Prinsip Kedaulatan Di Tangan Rakyat
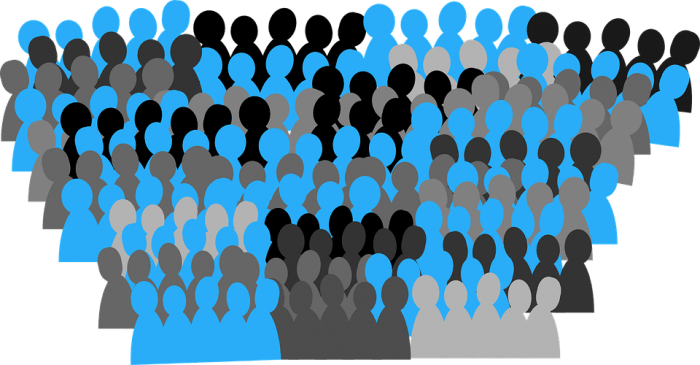
Oleh: Lukman Noerochim
Salah satu pemikiran mendasar dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai konsekuensi dari ide kedaulatan rakyat, rakyat melalui wakilnya dipandang memiliki hak untuk membuat konstitusi, peraturan dan undang-undang apapun; mereka pun berhak untuk membatalkannya. Dalam demokrasi semua standar dikembalikan pada akal manusia. Padahal faktanya, sehebat dan secerdas apapun, manusia tetaplah manusia; serba lemah, kurang, terbatas dan butuh akan yang lain. Fakta tersebut disadari sendiri oleh ahli hukum Barat seperti Prof. Dr. Angelius (Wijs Gerige Ge Menschapsleer). Dia mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan mutlak membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan manusia—termasuk hukum—pasti mengalami kekurangan dan kelemahan serta akan menimbulkan perbedaan, perselisihan dan pertentangan.
Istilah demokrasi berasal berasal dari kata demos artinya rakyat dan cratein yang berarti pemerintah. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai “Government of the people, by the people, for the people” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
Kemunculan demokrasi terinspirasi fakta negara kota (polis) di kota Athena, Yunani pada sekitar tahun 450 SM yang mempraktikkan pelibatan seluruh warga kota dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Yunani Kuno tersebut digali kembali di Eropa pada ‘zaman pencerahan’, yakni era perlawanan terhadap kekuasaan gereja dan kaisar (pada zaman pertengahan) yang sarat dengan penyimpangan dan penindasan terhadap rakyat dengan mengatasnamakan agama (baca: gereja). Oleh karena itu, muncullah gerakan reformasi gereja yang menentang dominasi gereja, dan menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. Puncaknya adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang berujung pada sekularisasi, yakni upaya kompromistik untuk memisahkan gereja dari masyarakat, negara, dan politik.
Pada masa itu, orang mencari suatu model agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang, keluarga kerajaan, kaum bangsawan atau penguasa gereja. Ironinya, satu-satunya bahan yang tersedia bagi para pemikir di Abad Pertengahan adalah dari sejarah Yunani Kuno. Dari sejarah itu mereka belajar bahwa di Kota Athena tempo dulu diterapkan satu sistem, yaitu seluruh warga kota turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sistem tersebut dianggap sistem yang baik oleh para pemikir Abad Pertengahan waktu itu. Mereka yang sedang tertekan oleh kediktatoran para raja dan kaum bangsawan serta penguasa gereja kemudian mengadopsi sistem Athena tersebut dan mempopulerkannya dengan nama “demokrasi”.
Menilik dari aspek historis, demokrasi jelas dilahirkan dari rahim sekularisme yang menolak campur tangan agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya negara. Selain itu, demokrasi juga murni berasal dari rekacipta dan hawa nafsu manusia, bukan berasal dari agama samawi manapun, apalagi Islam.
Dalam demokradi, peran akal sama sekali tidak dapat menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik (khayr) atau buruk (syarr), terpuji (hasan) atau tercela (qabîh). Hanya Allah (Asy-Syâri’) yang dapat menilai baik-buruk dan terpuji-tercelanya sesuatu. Alasannya, surga dan neraka adalah ciptaan Allah sebagaimana halnya manusia, langit dan bumi. Dalam hal ini, Allah telah menentukan kelayakan manusia memasuki surga atau neraka bergantung pada sejauh mana manusia mengikuti perintah-Nya. Artinya, surga-neraka atau pahala-siksa merupakan konsekuensi dari sejauh mana manusia mengikuti hukum-hukum Allah, Pemilik surga dan neraka, bukan mengikuti kehendak manusia sebagai makhluk-Nya dengan segala keterbatasannya. Manusia tidak memiliki kemampuan menilai perkara-perkara yang berada di luar jangkauan akalnya, bahkan ia tidak mungkin mampu menilai perkara-perkara yang tidak dapat dia indera.
Pada praktiknya di negara sekular, hukum dan perundangan (termasuk persanksian) dibuat berdasarkan cara pandang terhadap kemaslahatan para pembuatnya. Jika cara pandang mereka terhadap kemaslahatan berubah maka hukum pun dapat berubah, begitu seterusnya.
Selain itu, manusia cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum, sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang akan merugikan dirinya sendiri. Tentu realita tersebut sangat berbahaya mengingat penilaian terpuji-tercela, baik-buruk, pada diri manusia jelas berbeda. Kondisi itulah yang menyebabkan undang-undang buatan manusia sering dibuat, kemudian diperselisihkan, lalu dipertentangkan dan pada akhirnya akan dicabut jika dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman. Oleh karenanya, hukum tidak boleh berasal dari manusia. Hukum haruslah berasal dari Yang Mahasempurna, yakni dari Zat Yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Dialah Allah SWT.


