Kebijakan New Normal Yang Prematur
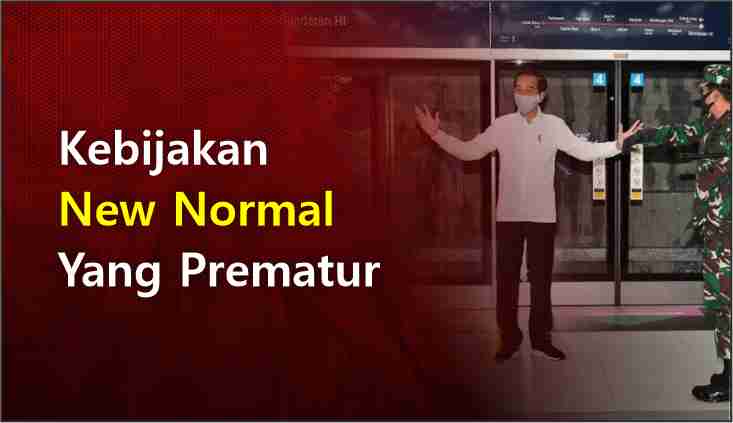
Akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo mewacanakan kebijakan New Normal pada masa wabah Covid-19. Dalam kondisi tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan, masyarakat dapat tetap beraktivitas sehingga mereka tetap produktif. Alasannya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan meski kurva kasus positif Covid-19 menurun, namun virus Corona tidak akan hilang. Jokowi juga mengumumkan 4 provinsi dan puluhan kabupaten/kota yang akan menjalankan new normal tersebut, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo (Koran Tempo, 1 Juni, 2020). Pusat-pusat bisnis di Jakarta, misalnya, telah siap untuk kembali beroperasi dengan menetapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Desakan Pengusaha
Istilah New Normal yang diwacanakan pemerintah sebenarnya bukan semata-mata perubahan gaya hidup masyarakat akibat pandemi Covid-19, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun, ia merupakan jargon untuk melegitimasi pembukaan kembali kegiatan bisnis-bisnis besar di tengah wabah Covid-19, seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, restoran dan pariwisata. Buktinya, kawasan yang ditujukan untuk New Normal adalah kawasan-kawasan yang masih berstatus merah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Jika ditelusuri, kebijakan New Normal tersebut merupakan bagian dari hasil lobi-lobi yang dilakukan pengusaha kepada pemerintah. Kamar Dagang Industri (KADIN), payung organisasi pengusaha di Indonesia, telah melakukan lobi-lobi intensif kepada Presiden dan sejumlah menteri agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan. Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, berpendapat bahwa Kamar Dagang dan Industri mendukung pengkajian pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar industri bergerak kembali. Menurutnya, daya tahan industri sudah semakin melemah selama pandemi virus corona (Kontan, 11/5/2020). Sementara itu, Ketua APINDO yang sebelumnya mengeluhkan jika arus kas pengusaha hanya bertahan sampai Juni, berpendapat pelonggaran PSBB memang tidak dapat dihindari mengingat daya tahan perusahaan dan masyarakat sudah sangat terbatas (Tempo.co, 13 Mei 2020).
Prematur
Kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial, yang selama sebenarnya masih sangat longgar, justru berpotensi memicu peningkatan kasus baru penderita Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, dari perspektif epidemologi, saat ini Indonesia belum layak untuk melakukan pelonggaran sosial. Penilaian yang dilakukan WHO per 2 Juni 2020, membuktikan hal tersebut. Menurut lembaga tersebut, ada tiga syarat pelonggaran pembatasan sosial, yaitu: terjadi penurunan kasus baru secara terus menerus setidaknya 50% selama periode tiga minggu sejak puncak; jumlah sampel tes yang positif untuk COVID-19 kurang dari 5%, setidaknya selama dua minggu terakhir; penurunan jumlah kematian di antara kasus yang dikonfirmasi dan yang mungkin terkena setidaknya selama 3 minggu terakhir.
Namun, dari penilaian WHO selama April dan Mei, seluruh provinsi di Jawa tidak memenuhi syarat tersebut. Lebih dari itu, kriteria tersebut tidak dapat diterapkan kecuali di Jakarta, lantaran tes minimal yang diperlukan adalah 1 per 1000 dalam seminggu. Dengan demikian, dua kriteria pertama tidak dapat diterapkan secara ideal. Jumlah kematian yang diumumkan pemerintah juga tidak dapat diterapkan secara ideal, sebab hanya pada pasien yang terkonfirmasi yang dihitung, sementara Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal tidak masuk dalam perhitungan tersebut.
Di samping itu, berdasarkan pendapat para ahli epidemiologi, pelaksanaan new normal ini baru boleh ketika angka penularan (basic reproduction number [R0] dan effective reproduction number [RT]) di bawah 1 dan hal itu harus stabil selama dua minggu. Jika angkanya masih di atas 1 maka potensi penularan masih ada sehingga berbahaya jika dilakukan new normal. Sayangnya, wacana new normal yang digaungkan Presiden Jokowi belum memenuhi kriteria tersebut. Angkanya masih naik turun sehingga berpotensi mengalami gelombang kedua yang lebih tinggi. Sekadar catatan, pada pertengahan Mei, angka RT DKI Jakarta masih di atas 1.
Lagi pula, turunnya angka penularan yang disampaikan oleh pemerintah merupakan dampak dari kebijakan pembatasan sosial selama ini. Dengan demikian, angka ini berpotensi bergerak naik kembali apabila perilaku sosial masyarakat dilonggarkan.
Tingginya angka penularan di Indonesia juga disebabkan oleh kurang seriusnya pemerintah untuk menambah fasilitas kesehatan penanganan Covid-19, seperti Alat Pelindung Diri (APD); ventilator; dan tes kit seperti, reagent dan tabung Virus Transfer Media (VTM). Jumlah ventilator saat ini sekitar 8.400 unit. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan lonjakan penderita yang mengalami gangguan pernafasan akibat Covid-19.
Dampak dari terbatasnya fasilitas penunjang penanganan covid-19 membuat pemerintah keteteran dalam melakukan tes. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil tes pasien. Sebagai contoh, untuk Kota Tangerang yang tesnya dilakukan di Jakarta memerlukan waktu 10-14 hari (Majalah Tempo, 1 Juni 2020). Akibatnya, banyak pasien, baik yang sudah dites ataupun yang belum, meninggal terlebih dahulu tanpa diketahui apakah dia positif atau tidak. Karena itu, dugaan bahwa jumlah di lapangan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikonfirmasi oleh pemerintah sangat beralasan.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kemampuan tes Indonesia memang sangat rendah. Menurut data dari laman worldmeters.info, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dites per 1 Juni 20120 baru 330 ribu orang atau 1,220 per satu juta penduduk. Jumlah itu sangat rendah jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai 17,343 per satu juta penduduk, dan Thailand yang mencapai 6,026 per satu juta.
Padahal, seperti yang dilaporkan oleh WHO, jumlah penduduk yang dites sangat menentukan kualitas data yang menjadi sumber acuan kebijakan pemerintah. Data yang tidak representatif akan menghasilkan pembacaan yang salah terhadap kondisi riil sehingga berpotensi memberikan input yang keliru bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Kebijakan Zalim
Pemerintah juga semestinya mengambil pelajaran dari negara-negara lain bahwa terburu-buru melakukan relaksasi hanya akan meningkatkan jumlah korban. Negara-negara yang melakukan relaksasi pembatasan sosial adalah negara-negara yang menunjukkan kurva kasus baru yang telah menurun secara persisten dari posisi puncak, seperti Cina, Taiwan, New Zealand, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Sebaliknya, beberapa negara berkembang yang mencoba melakukan pelonggaran di saat pandemi masih berkecamuk alias kurvanya masih bergerak naik, justru mengalami nasib yang tragis. Brazil, misalnya, mulanya bertindak cepat untuk melakukan lockdown untuk mencegah penularan virus Covid-19, namun keputusan pemerintah yang gegabah untuk melakukan pelonggaran membuat jumlah kasus baru di negara ini naik tajam. Hal serupa terjadi di Meksiko, dua hari setelah pemerintah mengumumkan normalisasi kegiatan ekonomi pada 1 Juni, jumlah penderita baru melonjak menjadi 3.891 kasus baru dari angka tertinggi bulan Mei sebesar 3.463.
Pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dengan alasan untuk memulihkan sendi-sendi ekonomi yang lumpuh meskipun menjadikan keselamatan rakyat sebagai taruhannya jelas sangat naif. Pasalnya, menjadi tugas negara untuk melindungi rakyatnya dari bahaya. Dan cara yang paling efektif adalah memutus mata rantai penyebaran virus melalui pembatasan sosial. Memang, beban fiskal yang ditanggung pemerintah semakin besar, namun hal ini tidak berlangsung lama jika dilakukan dengan ketat. Negara-negara lain yang telah berhasil melewati masa puncak virus ini hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan.
Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan pelonggaran yang berdampak pada meningkatkan kasus Covid-19, maka dampak ekonomi yang ditanggung pemerintah dan masyarakat secara luas akan semakin besar. Di samping itu, potensi terjadinya gelombang kedua yang lebih besar akan menyebabkan kenaikan permintaan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien baru. Padahal, beban tenaga medis dan fasilitas kesehatan saat ini sudah overload. Apalagi, tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, masih cukup rendah sehingga potensi penularan akan cukup tinggi. Karena itu, mereka dibiarkan mengatur diri mereka sendiri, maka sama saja membiarkan mereka untuk tertular virus tersebut.
Selain itu, lemahnya dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama masyarakat menengah bawah, berdampak pada tidak tertibnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Nilai Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak per keluarga, tidak berkesinambungan, dan hanya pada sebagian masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, rakyat terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan menanggung dua risiko: risiko lapar dan risiko tertular virus.
Dengan demikian, relaksasi regulasi pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan istilah New Normal yang dilandasi oleh motif ekonomi, sebagaimana desakan para pengusaha, merupakan tindakan yang zalim. Sebab, kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah rakyat yang terpapar virus ini. Sementara pada saat yang sama, pemerintah memberikan dukungan yang minim kepada tenaga medis yang bertarung di front terdepan penangan Covid-19.
Kebijakan tersebut jelas sangat membahayakan rakyat negara ini. Nabi saw bersabda:
“tidak boleh melakukan tindakan bahaya (mudarat) dan tidak boleh menyebabkan bahaya bagi orang lain.”
Selain itu, mengedepankan kepentingan pengusaha dibandingkan dengan nasib rakyat banyak juga sangat tidak adil. Risiko paling besar penularan akibat dibukanya kegiatan bisnis para pengusaha adalah para karyawan mereka dan para konsumen, sementara para pemilik bisnis dapat tetap aman terhindar risiko. Sikap pemerintah tersebut jelas bertolak belakang dengan konsep Islam yang mengatur bahwa tugas pemerintah adalah melakukan pelayanan terbaik pada seluruh rakyatnya termasuk dalam aspek kesehatan, tanpa pandang bulu, baik kaya ataupun miskin, pengusaha ataupun pekerja.
Oleh karena itu, dalam konteks ini, semestinya pemerintah memperkuat implementasi kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai virus; meningkatkan kemampuan tenaga medis untuk melakukan tes, menelusuri (tracing) pihak yang berhubungan dengan penderita hingga beberapa lapis, dan melakukan tindakan yang optimal kepada penderita. Bukan seperti saat ini, anggaran untuk penanggulangan Covid-19 hanya Rp87 triliun, sementara insentif untuk dunia usaha mencapai Rp121 triliun. Selain itu, pemerintah semestinya memberikan bantuan kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai kepada rakyat secara merata dalam jumlah yang layak hingga wabah ini dapat dikendalikan. Nabi saw bersabda:
“Pemimpin itu adalah pelayanan. Dan dia bertanggungjawab atas seluruh rakyatnya.”
Walhasil, kebijakan pemerintah melakukan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial dengan jargon New Normal, di saat kasus baru penderita Covid-19 masih tinggi, merupakan tindakan yang zalim yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika pemerintah tetap memberlakukan kebijakan tersebut, maka ini menjadi bukti kesekian kalinya bahwa penguasa saat ini lebih tunduk pada kepentingan para pebisnis dibandingkan mengurusi rakyatnya secara umum. Wallahu a’lam bi shawab [muis].