Refleksi 2024, LBH Pelita Umat Paparkan Gejala Autocratic Legalism
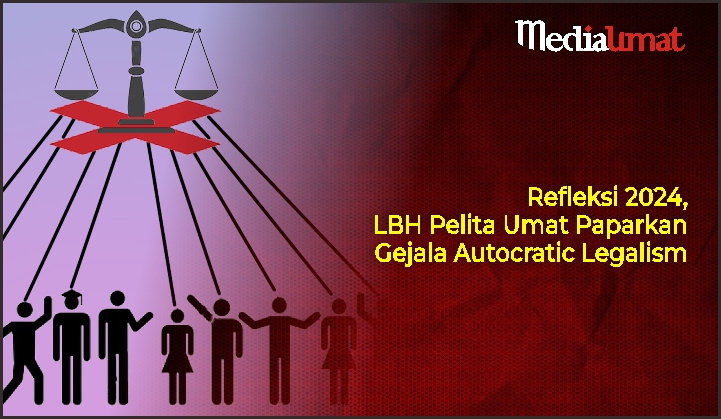
Mediaumat.info – Merefleksi penegakan hukum di negeri ini selama 2024, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan melihat ada gejala autocratic legalism.
“Hasil pengamatan kita pada tahun 2024 ini ada gejala yang kita sebut dengan autocratic legalism,” ujarnya dalam Fokus Spesial: Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Masa Depan Umat Islam, Selasa (31/12/2024) di kanal YouTube UIY Official.
Menurutnya, autocratic legalism adalah gaya kepemimpinan serta kendali penuh atas pengambilan keputusan oleh penguasa yang seolah-olah sesuai dengan hukum. Padahal hukumnya sudah ‘diakali’ terlebih dahulu.
“Kalau ada hal yang kemudian tidak sesuai, dia ubah supaya keinginan dia itu sesuai dengan hukum itu,” terangnya, masih mengenai praktik kekuasaan yang bisa mengarah pada terbentuknya rezim otoriter ini.
Sekadar ditambahkan, dalam konteks hukum modern, autocratic legalism juga dapat diartikan sebagai paradigma yang menggunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan, bukan sebagai alat keadilan. Praktik ini sering kali mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional itu sendiri.
Indikator
Indikatornya, ungkap Chandra, ruang kebebasan sipil dalam hal ini kebebasan menyampaikan ide, pikiran atau gagasan ke dalam ruang publik, terlebih untuk berkumpul atau berserikat yang makin menyempit.
Hal ini bisa dilihat dari upaya-upaya persekusi berupa penghadangan hingga pembubaran suatu pengajian hanya dengan dasar tuduhan yang sebenarnya tidak tepat.
Bertambah parah, imbuhnya, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penengah justru masuk ke dalam narasi yang dijadikan legalitas persekusi. “Dan yang menjadi parahnya adalah aparat penegak hukum masuk ke dalam narasi itu, yang mestinya dia sebagai wasit yang menengahi,” tandasnya.
Tak hanya itu, terkait indikator pertama, tentang gejala autocratic legalism tersebut, Chandra menyinggung seputar putusan bebas terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar pada kasus pencemaran nama baik di PN Jakarta Timur, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, di awal tahun 2024.
Kala itu, majelis hakim yang memutuskan tak bersalah pada Haris Azhar, membeberkan prinsip hukum yang dikenal dengan cogitationis poenam nemo patitur, suatu istilah yang bermakna ‘tidak ada hukuman untuk pemikiran.’
Artinya, terdapat prinsip yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan gagasan atau pikirannya ke dalam ruang publik tanpa perlu rasa takut atau dapat sanksi pidana.
Bahkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18, maupun Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19, sekalipun, prinsip ini kemudian diadopsi. Tak berhenti di situ, prinsip ini juga akhirnya diadopsi di dalam setiap negara, termasuk Indonesia.
Meski demikian, selama 2024 kondisi ruang kebebasan sipil di negeri ini secara fakta justru terancam pada masa pemerintahan Jokowi. Karena itu, Chandra berharap, di tahun 2025, di era pemerintahan Presiden Prabowo ruang kebebasan sipil semakin terbuka.
Indikator kedua, sambungnya, terjadinya kooptasi terhadap partai politik, atau dikenal dengan istilah koalisi parpol.
Pada mulanya, di negara yang mengaku menerapkan sistem demokrasi ini mengadopsi prinsip hukum yang membagi kekuasaan menjadi tiga (trias politica) yang maknanya kekuasaan negara tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja.
Tetapi lagi-lagi yang terjadi justru paradoks dengan terbentuknya koalisi ‘gemuk’ antar parpol. “Koalisi itu sebetulnya agak paradoks dari konsep John Locke yang tadi trias politica itu,” sebut Chandra, seraya memastikan mekanisme checks and balances untuk mengatur agar kekuasaan di dalam suatu negara tidak terpusat di satu bagian dan saling mengontrol satu sama lain enggak bakalan terjadi.
Masih berkenaan dengan koalisi, gejala autocratic legalism tampak pula ketika putusan tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, direvisi secara kilat oleh DPR dan pemerintah dalam waktu tak lebih dari sehari.
Pada 20 Agustus 2024, MK telah memutuskan untuk menurunkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta memberikan kepastian hukum terkait syarat usia calon kepala daerah yang dihitung sejak ditetapkan sebagai calon melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, bukan saat dilantik, sebagaimana putusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) beberapa saat lalu.
Makanya, secara substansi banyak pihak termasuk dirinya memandang DPR dan pemerintah ketika itu telah terang mengangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan kata lain, di tengah ketergesa-gesaan, DPR dan pemerintah telah memamerkan definisi sempurna dari sebuah istilah autocratic legalism, sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu sebuah tindakan otoriter yang dilakukan dengan cap hukum agar terlihat legal dan diterima.
Lengkap dengan cacat logika yang menyertai landasan revisi UU Pilkada di dalamnya. Barangkali dapat dipahami, sebab tindakan ini tidak lagi didasari oleh nalar hukum, melainkan berpijak pada nafsu kekuasaan semata.
Demikian, di dalam sistem demokrasi memang terdapat celah yang cukup besar untuk melakukan hal itu. “Di dalam sistem demokrasi, gejala autocratic legalism ini difasilitasi, bukan difasilitas, terdapat ruang yang begitu besar untuk melakukan itu,” pungkasnya.[] Zainul Krian


