Kiai Shiddiq: Pendapat Bolehnya Muslimah Berhaji Tanpa Mahram Tak Bisa Diterima
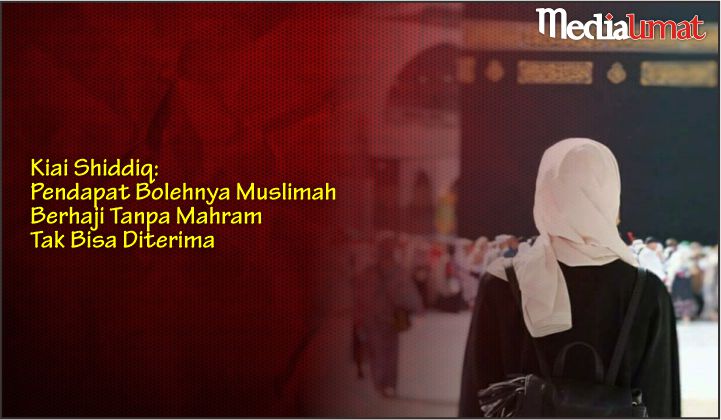
Mediaumat.id – Pakar Fikih Kontemporer sekaligus Founder Institut Muamalah Indonesia KH Muhammad Shiddiq al-Jawi menyampaikan, pendapat yang membolehkan Muslimah beribadah haji ataupun umrah tanpa didampingi oleh mahram tidak dapat diterima. “Pendapat yang membolehkan ini tidak dapat diterima,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Kamis (13/10/2022).
Pasalnya pemahaman itu bertentangan dengan makna dari hadits Ibnu Abbas ra. yang justru mengharamkan perempuan naik haji tanpa mahram.
Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (bersepi-sepi) dengan seorang perempuan, kecuali perempuan itu disertai mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali perempuan itu disertai mahramnya.”
Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri saya hendak berangkat haji, sedangkan saya telah diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu!” (HR Bukhari no. 1763 & 4935; Muslim no. 424 & 1341).
Sebelumnya seperti dikabarkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Selasa (11/10) melalui Menteri Taufiq bin Fauzan al-Rabiah, mengumumkan bolehnya Muslimah beribadah haji tanpa didampingi mahram.
Lantas seperti juga dikutip Arab News, Penasihat Layanan Haji dan Umrah Saudi Ahmad Saleh Halabi menyebut perempuan dimaksud cukup ditemani wanita terpercaya atau rekan yang aman untuk melakukan haji atau umrah.
Terlepas itu, kata Kiai Shiddiq, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama jika hajinya bersifat sunnah, yakni berhaji untuk kedua kalinya dan seterusnya, seorang perempuan naik haji tanpa mahram hukumnya tidak boleh. Hal itu ia kutip dari kitab Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz XVII, hlm. 35.
Adapun apabila hajinya bersifat wajib, yakni baru pertama kalinya naik haji, sambung Kiai Shiddiq, terdapat khilafiah di antara ulama menjadi dua pendapat.
Pertama, tidak boleh berhaji tanpa mahram, karena adanya mahram adalah syarat wajib bagi perempuan yang hendak berhaji. “Ini pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali,” jelasnya.
Lebih jauh para ulama mazhab Hambali berpendapat jika keberadaan mahram bagi perempuan merupakan bentuk istitha’ah atau kemampuan dari seorang wanita dalam ibadah haji. Secara otomatis jika mahramnya tidak ada, maka perempuan tersebut dianggap tidak wajib melakukan haji.
Kedua, boleh perempuan berangkat haji walaupun tanpa mahram, karena adanya mahram bukan syarat wajib.
“Pendapat ini membolehkan perempuan berangkat haji bersama rombongan perempuan yang terpercaya (niswah tsiqaat, rifqah ma`muunah),” terangnya, seraya menyebut ini pendapat ulama mazhab Syafi’i dan Maliki, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Juz XVII, hlm. 35-36.
Dalilnya yaitu hadits Adi bin Hatim ra, ia berkata, “Ketika aku berada bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya, dan seorang lagi mengadu bahwa jalan tidak aman. Nabi SAW lalu bersabda, ’Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Al-Hiirah?’ Aku menjawab, ‘Aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah diberitahu tentangnya’. Nabi SAW bersabda, ’Apabila kamu panjang umur, kamu benar-benar akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hiirah sampai ia thawaf di Ka’bah, sedang ia tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah’.” (HR. Bukhari no. 3400).
Namun kata Kiai Shiddiq, pendapat yang menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Juz VI, hlm. 549, itu memang menunjukkan bolehnya Muslimah naik haji tanpa disertai mahram, namun tidak dapat diterima berdasarkan dua sanggahan.
Pertama, hadits tersebut sekadar berita (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahwasanya kejadian tersebut akan terjadi, sebagai suatu tanda akhir zaman (dekatnya Hari Kiamat), tetapi tidak menunjukkan hukum halal atau haram.
Sementara Imam Nawawi di dalam Syarah An-Nawawi ‘Ala Muslim, Juz I, hlm. 159 juga menegaskan, ‘Tidak semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda Hari Kiamat itu menghasilkan hukum haram dan tercela’.
Kedua, andaikan benar pendapat yang mengacu hadits Adi bin Hatim ra tersebut menghasilkan hukum boleh, maka jelas akan bertentangan (ta’aarudh) dengan hadits Ibnu Abbas ra yang menghasilkan hukum haramnya perempuan naik haji tanpa disertai mahram atau suaminya, misalnya.
Pendapat Kuat
Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat (rajih), menurut Kiai Shiddiq adalah pendapat yang tidak membolehkan, karena telah terdapat nash hadits yang jelas (sharih) yaitu dari Ibnu ‘Abbas ra sebagaimana tadi diungkap.
“Hadits ini dengan jelas atau sharih menunjukkan bahwa keberadaan mahram atau suami adalah syarat wajib bagi perempuan. Sebab jika bukan syarat wajib, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan laki-laki itu untuk menemani istrinya naik haji dan meninggalkan kewajiban berperang,” jelasnya, sembari menyinggung makna QS al-Baqarah: 216 tentang jihad di jalan Allah SWT.
Pun di samping itu, kata Kiai Shiddiq, kaidah fikih telah menetapkan, bahwa suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban lain.
Dengan kata lain, ketika Nabi SAW memerintahkan laki-laki itu untuk meninggalkan kewajiban berperang, berarti hukum adanya mahram atau suami adalah wajib, bukan sunnah atau mubah.
Keterangan demikian seperti halnya dijelaskan oleh Imam Ali bin Nashir al-Syal’an di dalam kitab An-Nawazil fi Al-Hajj, hlm. 95; dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi di kitab Al-Asybah wa al-Nazha’ir, hlm. 148.
Sekadar diketahui, pendapat yang mengharamkan ini juga telah dipilih oleh Imam Taqiyuddin an-Nabhani. “Syariah telah melarang wanita dari safar (perjalanan selama sehari semalam atau lebih), walaupun perjalanan naik haji, tanpa disertai mahramnya,” ucapnya, mengutip fatwa beliau sebagaimana tertuang di dalam kitab Al-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam, hlm. 34.
Terlebih, untuk menilai yang paling rajih, dari dua hadits yang bertentangan diperlukan tarjih yang pada prinsipnya memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antaranya dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainya.
Pungkasnya, mengutip penjelasan Imam Taqiyuddin an-Nabhani di dalam kitab Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz III, hlm. 489, Kiai Shiddiq menegaskan, “Pendapat yang rajih atau lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkan, sesuai kaidah tarjih dalam ushul fiqih, yaitu ‘Hadits yang menunjukkan keharaman lebih kuat daripada hadits yang menunjukkan kebolehan’.”[] Zainul Krian


