Polemik Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta Bermula dari Sini
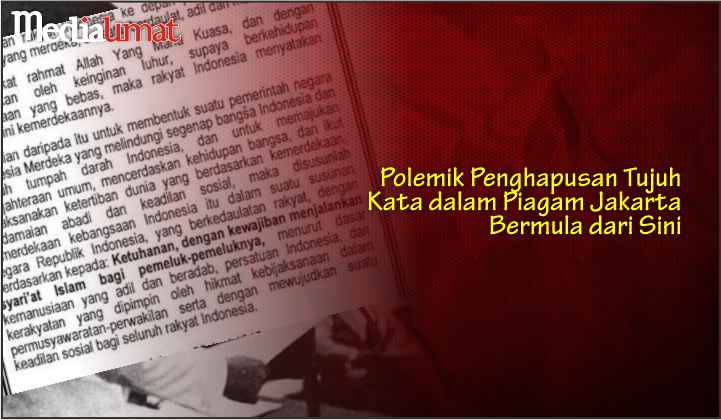
Mediaumat.id – Polemik penghapusan tujuh kata ‘Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’, dalam Piagam Jakarta, dinilai Filolog Salman Iskandar bermula dari peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945.
“Awal polemik ini bermula ketika apa? Ketika pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik ke Rengasdengklok oleh para pemuda nasionalis-sekularis dari kubu socialism-communism,” ujarnya dalam Kajian Sejarah dan Peradaban: Polemik Tujuh Kata Piagam Jakarta, Jumat (24/6/2022) di kanal YouTube Ngaji Subuh.
Adalah para pemuda progresif revolusioner marxisme atau mahasiswa kiri, di antaranya Chairul Saleh, Agus Wikana, Sukarni dan DN Aidit yang menculik dan mengasingkan kedua tokoh bangsa tersebut ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
Selama pengasingan dari Jakarta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, kata Salman, disinyalir ada lobi-lobi politik yang dilakukan mereka seputar Piagam Jakarta.
Penting diketahui, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah teks proklamasi kemerdekaan otentik yang nantinya harus dibacakan ketika Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka.
Artinya, jikalau publik mengetahui ada naskah proklamasi seperti hari ini dikenal, menurut Salman itu tidak otentik.
“Justru sebetulnya Piagam Jakarta 22 Juni itulah yang kemudian naskah proklamasi otentik yang nanti harus dibacakan ketika Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka,” tuturnya, mengutip pernyataan yang menurut Salman pernah disampaikan oleh Firdaus Ahmad Naqib dan Prawoto Mangkusasmito, pengurus besar Masyumi sebelum dibubarkan oleh Bung Karno.
Perlu diketahui pula, janji kemerdekaan memang telah disampaikan sebelumnya oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki, selaku Kepala Pemerintahan Kekaisaran Nippon yang ada di Tokyo, pada 7 September 1944 (18 Ramadhan 1363) dalam pidato politiknya.
“Dia (PM Koiso Kuniaki) kemudian memberikan janji berupa janji kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada wilayah-wilayah, negeri-negeri yang ada di wilayah Asia Timur Raya, termasuk juga dalam hal ini adalah Nusantara, Indonesia,” beber Salman, seraya membeberkan, bak gayung bersambut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta pada April 1945.
Selain itu, Piagam Jakarta memuat ketentuan syariat Islam sebagai dasar negara dan perundang-undangan, serta telah menjadi kesepakatan panitia sembilan yang dibentuk setelah sebelumnya tidak menemukan titik temu terkait rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPK.
Mereka adalah empat orang tokoh nasionalis sekuler dan empat tokoh nasionalis Islam yang dipimpin sendiri oleh Koesno Sosrodihardjo atau Soekarno (Bung Karno) yang menurut Salman, masih tergolong sebagai sosok dari kalangan nasionalis sekuler, bukan dari kalangan islamis.
“Tokoh-tokoh nasionalis sekuler ada sosok yang kita ketahui sebagai Mohammad Hatta, ada Ahmad Soebardjo, ada sosok yang disebut Mohammad Yamin, ada juga tokoh nasionalis sekuler yang berasal dari Manado orang Kristen Protestan, namanya adalah Alexander Andries Maramis,” sebutnya.
Sedangkan dari kalangan nasionalis Islam, KH Abdul Wahid Hasyim (PBNU), KH Kahar Muzakir (PP Muhammadiyah), KH Abikoesno Tjokrosuyoso (SI), dan KH Agus Salim (Partai Penyadar).
“Dari hasil kompromi dan sidang yang kemudian diselenggarakan oleh panitia sembilan maka terjadilah kesepakatan di antara mereka bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 1945 setelah sidang sekian lama, sidang sekian pekan, maka kemudian panitia sembilan bersepakat untuk menandatangani Piagam Jakarta yang kemudian dikatakan oleh Mohammad Yamin sebagai Jakarta Charter is a gentleman’s agreement,” urainya.
“Piagam Jakarta itu merupakan kesepakatan yang paling jantan di antara kedua belah pihak di antara dua kubu yang satu sama lain yaitu kemudian taken and given, kesepakatan yang harus kemudian ditetapkan,” tegasnya memaknai.
Di sisi lain, lanjut Salman, usai mendengar berita kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, para pemuda progresif revolusioner marxisme tersebut pun mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan janji dari Nippon seperti yang pernah diberikan.
Lantas terjadilah penculikan sebagaimana peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945 yang secara sejarah Indonesia, kata Salman, perlu diketahui masyarakat.
Namun pada sorenya, pada tanggal sama, Bung Karno dan Hatta dijemput Ahmad Soebardjo yang sebelumnya telah menyakinkan Chairul Saleh, Agus Wikana, Sukarni dan DN Aidit, bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan.
“Jangan khawatir, kami akan mengikuti apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian sampaikan. Tunggulah saja waktunya,” ucap Salman, menirukan Ahmad Soebardjo kala itu.
Mereka bertiga, yang notabene tokoh penandatanganan isi dari Piagam Jakarta dari kalangan nasionalis sekuler, pun tiba ke Jakarta pada 16 Agustus malam dan segera melobi Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk ikut mendukung berkenaan rencana menyegerakan proklamasi kemerdekaan.
“Laksamana Muda Tadashi Maeda pada waktu itu mempersilahkan mereka untuk mengadakan rapat di kediaman Tadashi Maeda pada tanggal 16 Agustus malam sampai tanggal 17 Agustus dini hari,” tandas Salman.
Sampai-sampai, sambungnya, Bung Karno, Hatta, Ahmad Soebardjo, dan para pemuda kiri tersebut tidak tidur oleh sebab merumuskan kembali naskah proklamasi kemerdekaan yang sebelum itu, sebenarnya sudah terbentuk berupa Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Saat itu, terang Salman, tiga kalangan nasionalis sekuler sempat saling bertanya perihal siapa di antara mereka yang membawa Piagam Jakarta. “Ternyata mereka bilang tidak sama sekali,” cetusnya.
Padahal, kediaman Hatta jaraknya paling dekat dengan kediaman Tadashi Maeda. “Cukup delapan sampai sepuluh menit itu bisa sampai untuk membawa Piagam Jakarta,” ucap Salman turut menyesalkan.
Artinya, tiga tokoh nasionalis sekuler yang sebelumnya sepakat dengan menandatangani isi dari Piagam Jakarta, akhirnya tidak menjadikannya sebagai naskah proklamasi kemerdekaan yang rencananya akan dibacakan di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, pada hari itu juga jam sepuluh pagi.
Tak Berhenti
Gerilya dan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh kalangan nasional sekuler tidak berhenti sampai di situ. Mereka, orang-orang non-Islam, terutama dari kalangan wilayah Indonesia Timur senantiasa berupaya melobi Bung Karno dan Hatta terkait isi dari Piagam Jakarta yang besar kemungkinan esoknya, 18 Agustus 1945 akan disahkan sebagai rumusan perundang-undangan.
Sebutlah sila pertama yang memuat klausul, “Negara berdasarkan atas dasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Ditambah dengan ketentuan mengenai kepala negara, yang dijelaskan bahwa presiden Indonesia adalah warga Indonesia asli dan beragama Islam.
“Mereka sangat tidak suka dan tidak berkenan dengan isi dari perundang-undangan dasar 1945 yang di situ juga memuat konten dari kesepakatan Piagam Jakarta 22 Juni 1945,” jelas Salman.
Apalagi di dalam Pasal 29 ayat pertama juga ditegaskan kembali bahwa negara Indonesia berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Menurutnya, mereka adalah mahasiswa kiri yang dikenal sebagai mahasiswa kedokteran Sekolah Tinggi Kedokteran yang berpusat di asrama Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku), Prapatan 10.
Kata Salman lagi, mereka diutus oleh perwakilan dari Indonesia Timur. Antara lain, Samuel Ratulangi, politisi Protestan dari Manado, Sulut; Johannes Latuharhary, dari Kepulauan Seram, Maluku; dan I Gusti Ketut Pudja, orang Hindu dari Bali yang mewakili kepentingan di Nusa Tenggara, yang sebelumnya mengetahui kalangan nasionalis sekuler penandatangan Piagam Jakarta pada waktu itu masih ajeg dengan pendiriannya untuk tetap akan memberlakukan dalam penyusunan perundang-undangan.
Namun pertanyaannya, sela Salman, apakah benar yang menemui Hatta, karena Bung Karno menolak dengan alasan lelah sebab kurang tidur sebelumnya, adalah perwakilan dari Indonesia Timur?
Terlebih disebutkan pula ada opsir Kaigun Nippon yang menyertai mereka di sore hari tanggal 17 Agustus 1945 ke kediaman Hatta.
“Hatta di dalam buku yang dia tulis yang judulnya adalah ‘Sekitar Proklamasi’, dia mengaku dan mengklaim bahwa ‘ada opsir Kaigun Nippon yang datang ke kediamanku di sore hari tanggal 17 Agustus yang menghendaki bahwasanya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu selayaknya dicoret saja karena menyakiti warga atau masyarakat dari wilayah pendudukan bala tentara Nippon yang dikuasai oleh Kaigun’,” ungkapnya.
Perlu dipahami, terang Salman, Kaigun adalah armada laut dari bala tentara Dai Nippon di negeri ini.
Ternyata, klaim Hatta perihal Kaigun Nippon yang menemuinya dibantah jelas oleh asisten Kaigun Nippon yang bertanggung jawab untuk mendampingi Laksamana Muda Tadashi Maeda.
Ia adalah Kolonel Shigetada Nishijima yang sebelumnya menyatakan, Kaigun, tentara armada laut yang ada di Jakarta itu tidak lebih dari jari tangan kalian, tidak lebih dari sepuluh orang.
Maknanya, wilayah teritorial Jakarta dan Pulau Jawa secara keseluruhan bukan dalam kekuasaan Kaigun, bala tentara armada laut Nippon, tetapi justru dikuasai oleh armada pasukan darat bala tentara Nippon.
Era itu, wilayah Indonesia memang terbagi atas dua wilayah. Wilayah Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan dikuasai oleh angkatan darat Jepang, seperti halnya sejarah telah mencatat.
Sedangkan Sulawesi dan Indonesia Timur, dikuasai oleh angkatan laut Jepang, yang kantor perwakilannya ada di Jakarta.
“Siapa pun yang bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan baik islamis ataupun nasionalis sekularis itu sepengetahuan dan sepertujuan kami,” ucap Salman kembali menirukan.
“Dan di sore hari tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak ada seorang pun opsir kaigun yang menemui Hatta,” terang sang kolonel, sebagaimana kesaksiannya yang masih tertulis rapi di arsip kesejarahan, sumber primer di Universitas Waseda, Tokyo, dengan judul Nishijima Collection atau koleksi kesaksian dai Kolonel Shigetada Nishijima.
Siapa yang Datang Menghadap Hatta?
Lantas, muncul pertanyaan, siapa sebenarnya orang-orang yang mendatangi Hatta pada 17 Agustus 1945 sore hari?
“Ada satu buku khusus yang membahas secara tegas dan rinci siapa saja mereka yang menemui Hatta di sore hari tadi dan satu di antaranya berpura-pura sebagai Kaigun Nippon,” jawab Salman, seraya menyebut judul buku Kilas Balik Revolusi Indonesia.
Piet Mamahit, Imam Slamet dan seorang lagi yang kata Salman, mungkin karena terbiasa bermain teater atau drama dijuluki dengan Can Cebhok, yang menemui Hatta sore itu.
Di dalam buku tersebut, malah menyajikan kesaksian para tokoh pelaku sejarahnya. “Di situ juga ada sosok yang kemudian disebutkan atau profil yang kemudian disebutkan sebagai Piet Mamahit yang pada tanggal 17 Agustus 1945 sore ikut mendampingi Imam slamet dan Can Cebhok tadi menemui Hatta,” bebernya.
Sedangkan menurut Ridwan Saidi, seperti dikutip dari Dr Sujono Martosewojo dkk, dalam buku Mahasiswa ‘45 Prapatan 10, anggapan bahwa ada opsir Jepang yang datang ke rumah Hatta pada petang hari tanggal 17 Agustus 1945 kemungkinan karena kesalahpahaman saja. Imam Slamet, mahasiswa kedokteran yang menemani Piet Mamahit menemui Hatta memang berpostur tinggi, rambut pendek, mata sipit, dan suka berpakaian putih-putih. Imam Slamet inilah yang kemungkinan dikira sebagai opsir Jepang oleh Hatta.
Dengan demikian Salman pun melempar pertanyaan lagi, yakni apakah Hatta hanya mengarang cerita ataukah berdusta kepada bangsa Indonesia bahwa sore hari itu ditemui oleh opsir Kaigun Nippon?
Padahal, mengutip pernyataan Prof. Dr. Deliar Noer, M.A., yang menurut Salman, mengutip pula dari ucapan KH Kahar Muzakir ketika beliau bertanya kepada Alexander Andries Maramis, atau AA Maramis perihal Piagam Jakarta, ternyata tokoh Kristen Protestan asal Manado tersebut setuju hingga 200 persen.
“Mister Alexander Marawis pada waktu itu menjawab, kami orang-orang Kristen setuju 200 persen dengan isi Piagam Jakarta. Kami tidak setuju jika kami mengatakan seratus persen saja, tetapi kami itu setuju sepuasnya 200 persen. Kami setuju dengan isi Piagam Jakarta karena syariat Islam tidak diberlakukan bagi kami. Syariat Islam hanya berlaku bagi pemeluk-pemeluknya,” ungkap Salman.
Hatta Lobi KH Abdul Wahid Hasyim?
Klaim selanjutnya, masih dari Bung Hatta, bahwa ia mengaku telah melobi tiga perwakilan dari kalangan Islam yang termasuk panitia sembilan sebelum mencoret tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 pagi.
“Pertanyaannya bagi kita, Hatta menyatakan bahwa satu dari perwakilan Islam itu adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, namanya adalah KH Abdul Wahid Hasyim,” tutur Salman.
Padahal seperti diketahui, dalam notulensi kehadiran yang disusun sendiri oleh Abdoel Gaffar Pringgodigdo waktu itu, yang sebelumnya juga menuliskan kehadiran dalam sidang PPK yang menggantikan BPUPK, nama KH Abdul Wahid Hasyim tidak hadir di tempat pada 18 Agustus 1945.
Justru yang hadir adalah Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo yang memang dari kalangan nasionalis Islam, namun mereka bertiga tak termasuk yang menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Selanjutnya, Salman pun kembali melempar pernyataan terkait keberadaan KH Wahid Hasyim yang ketika itu, kata Hatta, ikut terlibat dalam lobi-lobi politik pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta.
“Ternyata KH Abdul Wahid Hasyim tidak ada di tempat,” timpalnya.
Apalagi di dalam upaya lobi-lobi politik yang dilakukan Hatta yang sangat singkat tersebut, karena memang datang ke lokasi sekitar jam delapan pagi hingga waktu pencoretan tujuh kata dimaksud jam 10, ternyata meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar berkenan ikut melakukan pencoretan.
“Namun Ki Bagus Hadikusumo begitu kukuh dan kokoh mempertahankan isi dari Piagam Jakarta,” sebutnya.
Bahkan Pimpinan Muhammadiyah tersebut justru secara tegas mengatakan ingin mengembalikan aspirasi Islam dan kaum Muslim di negeri ini dengan pernyataan, ‘Negara Indonesia berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ‘titik’. Kami tidak perlu kata-kata atau istilah bagi pemeluk-pemeluknya’.
Namun usai Hatta meminta kesediaan Kasman Singodimedjo untuk ikut melobi pimpinannya di Muhammadiyah tersebut, dengan kebesaran hati Ki Bagus Hadikusumo menerima usulan dari kalangan nasionalis sekuler mengganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
“Maka kemudian Ki Bagus Hadikusumo bertanya, apakah yang Mahaesa itu adalah konsepsi tauhid, Allahu Ahad? Maka Hatta menyatakan, benar,” cetus Salman.
Terlebih Bung Karno dan Hatta menjanjikan kepada tokoh-tokoh dari kalangan nasionalis Islam, ketika kelak dalam keadaan damai sekira enam bulan ke depan, akan diadakan sidang untuk merumuskan kembali dasar negara sekaligus perundang-undangan negara.
Klarifikasi
Berkenaan keberadaan KH Abdul Wahid Hasyim pada 17 dan 18 Agustus 1945, Salman menyampaikan, telah jelas klarifikasi dari istri beliau, Nyai Shalihah Munawarah binti KH Bisri Syansuri, sekaligus ibunda Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Pak kiai sedang ada di Jombang, sedang mengadakan acara bersama PBNU dan kami pun, istrinya, ikut menyertai sebagaimana istri-istri dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tanggal 17 Agustus itu kami sedang ada acara dan dipastikan Bapak Kiai sedang ada di Jombang bersama kami”, demikian jawaban Nyai Shalihah ketika ditanya Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menyengaja datang ke Jombang untuk mewawancarai beliau seputar keberadaan Sang Kiai pada hari-hari dimaksud.
Lebih lanjut, Nyai Shalihah juga menyampaikan, setelah mendapatkan berita dari radio di sore harinya bahwa Indonesia telah merdeka, sekaligus anggota PPK diminta untuk segera berangkat ke Jakarta, jam sepuluh malamnya mereka pun berangkat ke Stasiun Jombang untuk menunggu kedatangan kereta api dari Surabaya dengan tujuan Gambir, Jakarta.
Dengan kata lain, Nyai Shalihah Munawarah menyatakan bahwa jam 10 malam masih menunggu kedatangan kereta api dari Surabaya. “Kalau dulu (memang) bisa berjam-jam, karena keretanya tidak secanggih hari ini,” jelas Salman.
“Apakah tanggal 18 Agustus jam sepuluh pagi Pak Kiai Abdul Wahid Hasyim sudah tiba Jakarta ataukah tidak?” sambung Salman, seperti yang dilontarkan Yusril masih terkait keberadaan Sang Kiai yang sekali lagi menurut pengakuan Hatta kala itu juga dimintai persetujuan perihal pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta.
“Dik, mustahil kereta pada zaman itu tahun 40-an begitu cepatnya sampai ke Jakarta. Tidak mungkin Pak Kiai hadir tanggal 18 Agustus jam sepuluh pagi, enggak mungkin,” respons Nyai Shalihah.
Makin menegaskan, pernyataan Nyai juga telah dibenarkan oleh Gus Dur, putra beliau yang juga mengklarifikasi keberadaan ayahnya yang baru tiba di Jakarta pada 19 Agustus 1945.
Artinya, pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 memang tidak disaksikan oleh KH Abdul Wahid Hasyim, yang notabene anggota panitia sembilan dari kalangan nasionalis Islam yang turut menandatangani.
“Maka pertanyaannya bagi kita apakah kemudian pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu tetap kesepakatan?” tanya Salman.
Sebabnya, dari kalangan nasionalis Islam yang turut menandatangani isi dari Piagam Jakarta yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kesepakatan bersama di antara para founding father, tidak satu pun yang ikut menyaksikan pencoretan tujuh kata tersebut.
Tak ayal, atas itu, Budayawan Betawi Babe Ridwan Saidi yang diketahui pernah menjabat ketua umum pengurus Himpunan Mahasiswa Islam tahun 50-60-an menyatakan, sosok Hatta untuk urusan Piagam Jakarta adalah pendusta.
“Dengan segala penghormatan kami kepada sosok proklamator Bung Hatta kami menghormati, menyayangi dan memuliakan Bung Hatta dengan segala kesederhanaan dan kejujurannya. Namun mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, untuk urusan Piagam Jakarta sungguh Bung Hatta telah berdusta,” ucap Salman menirukan.
“Itu yang dinyatakan Babe Ridwan di dalam salah satu bukunya Risalah Kemerdekaan kalau tidak salah judulnya,” imbuhnya.
Dengan demikian, menurut Salman, pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sudah sesuai dengan visi dari kubu nasionalis sekuler semenjak awal ketika mereka berembuk untuk merumuskan dasar negara.
Penyesalan Kasman
Terakhir, mengenai sosok Kasman Singodimedjo yang sebelumnya turut melobi pimpinannya, Ki Bagus Hadikusumo untuk merelakan pencoretan tujuh kata dimaksud, akhirnya merasa menyesal.
“Di dalam bukunya itu beliau menyatakan penyesalannya yang luar biasa,” lontar Salman, seraya menyebut judul bukunya, Kasman Singodimedjo: Hidup Itu Berjuang.
‘Sayalah yang ikut bertanggung jawab dalam masalah ini dan semoga Allah mengampuni dosa saya’, demikian pernyataan Kasman Singodimedjo yang atas permintaan Hatta, ikut melobi Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima usulan pencoretan tujuh kata tersebut.
“Kenapa? Karena dia ingin menebus dosanya tadi,” pungkasnya.[] Zainul Krian